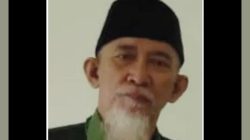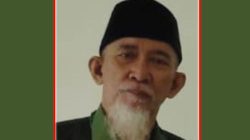Oleh: MA Silmi, S.Sos
Pemerhati Kebijakan Publik
Dari Pernyataan Kontroversi hingga Gelombang Donasi Demonstrasi
Polemik di Kabupaten Pati bermula dari kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Secara formal, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan menyesuaikan tarif pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, bagi masyarakat, terutama di tengah ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, kebijakan ini terasa menekan.
Ketegangan semakin memuncak ketika Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan pernyataan yang memicu gelombang reaksi. Dalam sebuah kesempatan, ia menantang warga untuk mengerahkan 50.000 orang jika ingin berdemo menolak kebijakan tersebut. Bukannya meredam, ucapan itu justru dianggap sebagai “tantangan” oleh publik. Media sosial segera dipenuhi unggahan warga yang mengajak berpartisipasi. Donasi mulai mengalir untuk mendukung logistik dan transportasi massa, dengan rencana aksi turun ke jalan pada 13 Agustus 2025.
Fenomena ini menunjukkan bahwa di era keterbukaan informasi, satu pernyataan dari seorang kepala daerah bisa menjadi pemantik besar. Pesan yang mungkin dimaksudkan sebagai keteguhan sikap, dalam persepsi publik bisa dibaca sebagai bentuk arogansi. Apalagi, ruang digital memungkinkan mobilisasi opini publik dalam hitungan jam.
– _*Evaluasi Statemen: Demokrasi, Komunikasi Publik, dan Vox Populi Vox Dei*_
Dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsep vox populi, vox dei—“suara rakyat adalah suara Tuhan”—menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan hanya akan bertahan jika selaras dengan aspirasi masyarakat. Mengabaikan atau meremehkan suara publik sama saja dengan meruntuhkan fondasi legitimasi itu sendiri.
Teori komunikasi publik dari Harold D. Lasswell (The Structure and Function of Communication in Society, 1948) menekankan bahwa komunikasi efektif harus menjawab: who says what in which channel to whom with what effect. Dalam kasus ini, “who” adalah seorang bupati—figur otoritas dengan bobot politik. “What” adalah tantangan kepada rakyat, yang secara sosial dapat dipersepsikan konfrontatif. “Channel”-nya adalah media massa dan media sosial, yang sifatnya memperbesar gaung pesan. “Effect”-nya bukan pemahaman atau penerimaan kebijakan, melainkan mobilisasi perlawanan. Artinya, terjadi kegagalan dalam desain pesan (message design) dan pengelolaan efek (effect management).
Dari sisi kepemimpinan, James MacGregor Burns dalam Leadership (1978) membedakan transactional leadership—yang fokus pada pertukaran kepentingan—dan transformational leadership—yang membangun visi dan menginspirasi. Pernyataan Bupati Pati terkesan transactional, menegaskan posisi kekuasaan, namun mengabaikan pendekatan transformational yang dapat meredam konflik dengan visi bersama dan empati publik.
Kepemimpinan di era demokrasi bukan hanya soal membuat kebijakan, tetapi juga mengelola persepsi publik. Satu kalimat yang keluar tanpa perhitungan matang dapat mengubah perbedaan pendapat menjadi perlawanan terbuka.
– _*Refleksi bagi Pemimpin Daerah Lain*_
Kasus di Pati memberi tiga pelajaran penting bagi para kepala daerah.
Pertama, kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat memerlukan strategi komunikasi yang matang. Teori Two-Step Flow of Communication dari Lazarsfeld dan Katz menunjukkan bahwa pesan sebaiknya disampaikan melalui opinion leader yang dipercaya warga sebelum diumumkan luas, agar interpretasi publik tidak liar.
Kedua, setiap pernyataan publik adalah bagian dari strategi kepemimpinan. Di era digital, pesan yang disampaikan pemimpin tidak pernah “lisan” semata—selalu ada potensi direkam, disebarluaskan, dan ditafsirkan ulang. Oleh karena itu, etika komunikasi publik menjadi bagian dari etika kepemimpinan.
Ketiga, vox populi harus ditempatkan sebagai kompas moral. Mendengar aspirasi publik bukan sekadar kewajiban formal, melainkan syarat mutlak keberlanjutan kepemimpinan. Respon cepat, bahasa inklusif, dan kesediaan berdialog memperkuat kepercayaan publik, bahkan ketika kebijakan sulit diterima semua pihak.
Polemik ini membuktikan bahwa kepemimpinan bukan ajang adu kekuatan, melainkan seni membangun kesepahaman. Keberanian seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa lantang ia menantang pihak berseberangan, tetapi dari kemampuannya merangkul mereka yang berbeda pandangan. Dalam demokrasi, suara rakyat bukanlah ancaman—melainkan sumber legitimasi yang menentukan apakah seorang pemimpin akan dikenang sebagai pembela rakyat atau sekadar penguasa yang lewat.